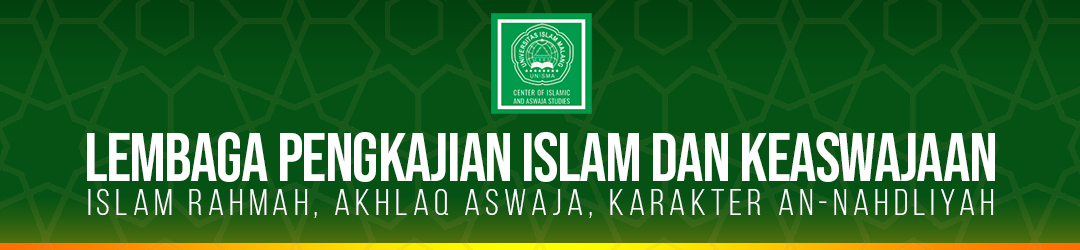99 Kyai Kharismatik NU
KH. MA’SUM
LASEM
Wafat: 1972 M / 1392 H
SANTRI-SANTRINYA
Muhammadun yang berganti nama Ma’sum sewaktu menunaikan ibadah haji (1900-an) telah menemukan dunianya, selama 54 tahun dari usianya, ia habiskan untuk membina dan mendidik santri. Dunia inilah yang kemudian mengangkatnya menjadi ulama besar. Di hari tuanya, namanya semakin harum karena jerih payahnya selama memimpin pesantren terlihat hasilnya. Alumnì pesantren Al-Hidayah banyak yang berhasil menjadi ulama besar, seperti KH. Mahrus Ali Kediri, KH.M. Bishri Syansuri dari Jombang, KH. Muslikh dari Mranggen, KH. Musthalih Badawi dari Kesugihan Cilacap, KH. Mustamid Abbas dari Buntet Cirebon, H. Ali Ma’sum puteranya sendiri, KH.Syaefuddin Zuhri, KH. Achmad Syichu, H. Mukti Ali, dan KH. Yusuf Hasyim.
Di mata para santri, Mbah Ma’sum adalah pribadi yang mulia, ia tidak pernah membeda-bedakan santrinya. Sikapnya lembut, tegas, dan garang adalah sikap yang padu dalam metodologi pendidikan dan mengajar yang diterapkan. Istiqamah dan bersahaja merupakan ciri utama kehidupan sehari-hari. Para santri merasa mendapat bimbingan setiap hari, siang dan malam. Bahkan santri yang sudah pulang ke kampung masih merasakan hal yang sama sebab Mbah Ma’sum termasuk rajin bersilaturrahmi ke rumah para santri.
POLITIK NON-KOOPERATIF
Mbah Ma’sum adalah figur ulama yang lahir pada masa hitamnya sejarah bangsa. Belanda mengenalkan sistem pendidikan modern ala Barat, para ulama pejuang mengambil sikap minggir, hijrah ke pedalaman. Politik non-kooperatif, sikap kebanyakan kaum santri waktu itu, akhirnya rnelahirkan sistem Pendidikan alternatif yang khas. Mereka mendirikan surau-surau kecil, kelak populer dengan sebutan pesantren sebagai pusat pendidikan.
DUNIA POLITIK
Di kalangan ulama Sunni, konsep Nashbul Imamah (mendirikan pemerintah) sangat populer, sebaliknya, Azlul Imam (memecat penguasa) kurang populer. Nashbul Imam di kalangan ulama Sunni hukumnya wajib pada zaman penjajahan, di samping Nashbul Imam yang menjadi tren perjuangan juga jihad fi sabillilah dalam mengusir penjajah.
Sebagai salah seorang ulama Sunni, Mbah Ma’sum tidak bisa lepas dari bingkai politik Sunni di atas. Dan itu dilaksanakan dalam bentuk penjuangan fisik yang nyata. Pada masa sebelum kemerdekaan, Mbah Ma’sum bersama pejuang lain melakukan jihad gerilya melawan penjajah Belanda di berbagai daerah pendudukan. Terutama di daerah pedalaman Lasem Rembang, Tuban dan sekitarnya.
Setelah kemerdekaan, Mbah Ma’sum di samping mengasuh pesantren juga aktif dalam dunia politik. Organisasi politik yang dipilihnya adalah NU. Menurutnya, NU yang pada tahun 195 menjadi partai politik cukup representatif untuk mewakili aspirasi umat Islam.
TERMASUK PENDIRI NU
Sebagai salah seorang yang mendirikan NU Mbah Ma’sum merasa ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan perjuangan NU, baik sebelum ataupun sesudah menjadi partai politik. Karena keaktifannya itu Mbah Ma’sum memperoleh kesempatan menjadi anggota konstituante mewakili NU meskipun kemudian memilih berhenti karena fisiknya yang mulai uzur.
Setelah berhenti dari keanggotaan konstituante, Mbah Ma’sum tetap aktif dalam aktifitas partai NU. Dalam pertemuan-pertemuan tingkat nasional, Mbah Ma’sum selalu hadir. Dalam kesempatan terakhir, meski dalam kondisi lemah ia masih menghadiri muktamar partai NU di Surabaya pada 1971, setahun sebelum ia wafat.
KISI MENARIK BERSAMA PROF. Dr. MUKTI ALI
Begitu setianya pada NU, sampai-sampai ia mengidentikkan diri dengan NU. Pendeknya, kejayaan NU adalah kebahagiaannya dan kehancuran NU adalah kehancurannya juga. Sikap seperti itu misalnya dapat dilihat dari nasihat yang pernah ia sampaikan kepada muridnya Prof. Dr. Mukti Ali, yang waktu itu menjabat Menteri Agama ketika berkunjung ke Lasem.
Dalam kesempatan tersebut Mbah Ma’sum berkata, “Kamu jangan membenci NU, karena membenci NU berarti membenci aku. Tapi jangan pula membenci Muhammadiyah, PNI, dan partai lainnya. Sebagai menteri, kamu harus berbuat adil kepada mereka”.
PEMBERONTAKAN PKI
Peristiwa G 30 S PKI 1965 untuk menggulingkan kekuasaan yang sah dengan kekerasan merupakan tragedi nasional yang tak pernah terlupakan sepanjang sejarah. G 30 S PKI sesungguhnya merupakan pengkhianatan yang kedua kalinya. Pengkhianatan pertama terjadi pada tahun 1948 di Madiun yang kemudian dikenal dengan peristiwa Madiun Affair. Pada tahun 1948 PKI berhasil menghimpun kekuatan, terutama di Jawa Timur, dan membunuh semua orang yang menghalanginya. Banyak ulama yang gugur oleh keganasan PKI. Dua hari setelah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI, partai NU sudah mengambil sikap tegas ketika kekuatan lain masih bingung menentukan sikapnya. G 30 S tidak lain adalah gerakan pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah oleh PKI. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PBNU menuntut agar PKI dibubarkan. HM. Subchan ZE, politikus muda berbakat memobilisasi massa membentuk Front Pancasila dari berbagai unsur kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama menuntas PKI.
Pergolakan politik di akhir tahun 1965 itu bukan saja terjadi di ibu kota RI, tetapi juga melanda di berbagai daerah di Nusantara. Dalam usaha penumpasan PKI Mbah Ma’sum memiliki andil yang cukup besar. Rumah dan pesantrennya diserahkan untuk dijadikan markas komando dan strategi aksi penumpasan PK1. Bukan saja pemuda Anshor, IPNU dan IPPNU yang berkumpul di masrkas baru itu, melainkan juga unsur Muspika setempat, pemuda Muhammadiyah dan PlI. Pada saat itu kegiatan pemerintahan, terutama yang menyangkut keamanan praktis pindah dari pusat pemerintahan Lasem ke rumah Mbah Ma’sum. Semua unsur Muspika, kecuali Danramil Asyik, pindah ke pesantren Mbah Ma’sum. Asyik ternyata terlibat G 30 S PKI dan tetap di markasnya membentuk kekuatan sendiri menghadapi markas pesantren.
Sementara itu, Mbah Ma’sum meninggalkan Lasem membangun kekuatan lain di luar Lasem. Sikap ini sering disalahpahami sebagai sikap takut terhadap PKI yang memang cukup kuat di Lasem. Yang dimaksud dengan kepergian Mbah Ma’sum sebenarnya adalah untuk mengunjungi santri-santrinya di berbagai daerah, kebiasaannya selama ini memberikan semangat dan dorongan untuk membentuk barisan perlawanan terhadap PKI di daerah tersebut. Santri santri yang dikunjungi tidak hanya di daerah Lasem, tapi juga di Jawa Timur. Kepada para santri yang didatangi satu persatu, Mbah Ma’sum menanamkan keberanian dalam hati para santri untuk melakukan jihaad fi sabilillah, hidup dengan tenteram atau mati sebagai syahid.
MELANGGAR FATWA SENDIRI
Bila ada kiai yang melanggar fatwanya sendiri, Mbah Ma’sum adalah orangnya. Kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda yang terlalu tinggi membuatnya lupa akan haramnya mengenakan dasi yang pernah difatwakan. Imran Hamzah, Ketua NU Lasem waktu itu, pada suatu kesempatan bersama sejumlah pemuda dan gerakan pemuda Anshor, menghadap Mbah Ma’sum. Mereka mengeluh karena tidak mempunyai pakaian seragam, sedangkan organisasi tidak mempunyai dana. Mbah Ma’sum mendengar keluh itu. Dengan caranya sendiri, keesokan harinya, pakaian seragam sudah tersedia.
“Imran, apakah pakaian sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak Anshor?”, tanya Mbah Ma’sum.
“Kemarin malah sudah dipakai latihan baris- berbaris” “Tapi”, dengan agak ragu Imran Hamzan mengemukakan masalah lain. “Anak-anak masih mengeluh, Mbah”.
“Butuh apalagi?”
“Anu Mbah, anak-anak usul minta dibelikan dasi warna hijau”.
Dasi hijau adalah salah satu kelengkapan seragam Anshor.
“Mereka kalau memakai pakaian seragam dengan dasi hijau tampak lebih gagah dan berwibawa”, sambung Imran meyakinkan.
“Kowe kabeh dhaif temen, usaha dasi kok ora biso. Aku moh dikon nggolek dasi” (Kalian semua lemah sekali. Usaha dasi saja nggak bisa. Aku tidak mau disuruh mencari dasi).
Tampak Mbah Ma’sum tidak tega melihat ekspresi wajah Imran yang memelas ketika itu.
“Yen gelem. satir itu gawanin dasi” (Bila mau, buatlah kain satir itu sebagai dasi), sambung Mbah Ma’sum. Sambil menunjuk kain satin di ruang tamu. Satir yang dimaksud adalah kain panjang yang membentang di ruang tamu sebagai pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Kebetulan warnanya hijau, persis warna dasi keinginan pemuda Anshor itu.
Tanpa dikomando, Imran Hamzah langsung mengambil kain satir. Terang saja Mbah Nyai Ma’sum uring-uringan. “Lho, kain satirku kok malah diambil? Nanti tamu-tamu saya kelihatan dari luar”.
“Biarkan saja, Nyai. Kain satir itu mau dibuat dasi Anshor, besok saya carikan gantinya”, Mbah Ma’sum membujuk. Akhirnya pemuda Anshor Lasem memakai dasi bekas kain satir. Di samping itu, Mbah Ma’sum juga mengusahakan peralatan Drum Bend Anshor Lasem. Kepedulian Mbah Ma’sum terhadap pembinaan generasi muda sangat besar. Perhatiannya kepada generasi muda bersifat langsung menyentuh persoalan. Menurutnya, generasi muda yang sampai menjadi korban hanya oleh kefakiran. Itu sebabnya, Mbah Ma’sum melaksanakan program anak asuh. Santri miskin dibebaskan dari biaya pendidikan dan segala kebutuhannya ditanggung. Bahkan bila ada santri yang berbakat, diberikan beasiswa untuk dikirim ke pesantren lain.
WAFATNYA
Ketika itu bulan Syawal 1390 (1970 M), KH. Baidhawi, paman dari pihak istri sedang sakit keras. Mbah Ma’sum menjenguknya di Lasem. Dalam kesempatan itu ia berkata, “Sampeyan jangan meninggal dahulu, banyak masalah yang perlu diselesaikan. Kalau sampeyan meninggal, dua tahun lagi saya akan menyusul”.
Memang bernada kelekar, tapi ungkapan itu menjadi kenyataan. Pada tahun 1970 itu Mbah Ma’sum jatuh sakit. Pada tanggal 20 Oktober 1972, kiai yang tak pernah meninggalkan shalat malam itu wafat setelah dirawat di Rumah Sakit Kariadi Semarang. la dimakamkan di samping Masjid Jami’ Lasem.
Mobil itu berjalan pelan di jalan raya. Hari Jum’at bulan Ramadhan, matahari memanggang jalan aspal kota Lasem. Panas sangat terik, adzan jum’at baru saja selesai, ketika mobil Chefrolet tua itu berhenti persis di depan masjid yang sudah penuh dengan para jamaah. Pintunya terbuka tapi tidak ada penumpang yang turun. Pintu dibiarkan terbuka hingga Shalat Jum’at selesai. Orang tahu di dalam ada Mbah Ma’sum terlentang di jok. Tubuhnya sangat lemah karena sakit usia lanjut. Dengan gerakan isyarat, ulama yang masih keturunan sayyid itu melakukan Shalat Jum’at dalam mobil. Dalam kondisi uzur, Mbah Ma’sum tetap melaksanakan Shalat Jumat.
Itulah terakhir kali Mbah Ma’sum menyapa kaumnya. Sepulang Jum’atan, tepat jam 14.00, 20 Oktoher 1972 yang bertepatan dengan 12 Ramadhan 1392 H. Mbah Ma’sum menghadap kembali ke sisi Allah dalam usia 102 tahun.
Sebelum wafat, Mbah Ma’sum sempat memanggil anak cucunya dan meninggalkan pesan. Pesannya antara lain minta kepada anak cucunya agar mencintai fakir miskin dan selalu tolong menolong dengan sesama. “Lanjutkan pesantren ini dengan ketekunan dan kesabaran dalam mendidik para santri. Peliharalah kerukunan dan jauhilah perselisihan di antara sesama”, demikian pesannya.
Dikutip dari: Buku 99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid 2 (Pustaka Anda Jombang, 2010)