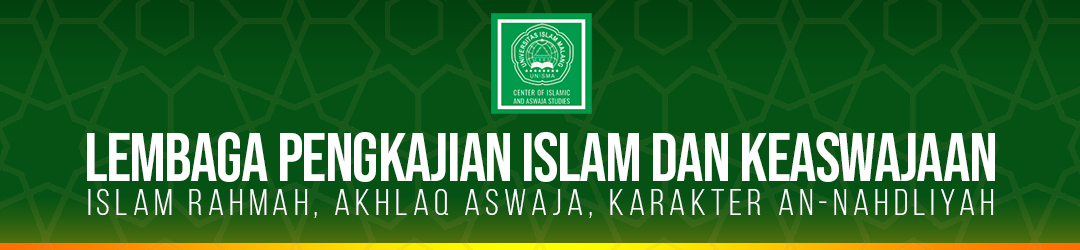99 Kyai Kharismatik NU
KH. MAHRUS ALI
LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR
WAFAT : 1405 H / 1985 M
KELAHIRANNYA
KH. Mahrus Ali lahir di Dukuh Gedongan, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1906 dengan nama Rusydi Tidak diketahui secara jelas mengenai hari, tanggal, dan bulan kelahirannya. Ayahnya bernama, Kiai Ali (putra Kiai Abdul Aziz, pengasuh pesantren Wotbogor Singaraja Indramayu, Jawa Barat). Sementara ibunya bernama Nyai Chasimah (putri seorang ulama besar di Jawa Barat pada akhir abad XVII yang bernama Kiai Sa’id). KH. Mahrus Ali merupakan anak terakhir dari sembilan bersaudara yang masing-masing bernama Kiai Mukhtar, Kiai Ahmad Afifi, Nyai Harmalah (Mulya), Nyai Mushlichah, Nyai Ismatul Maula, Jalaluddin, Kiai Yazid, Kiai Bilal, dan Kiai Mahrus Ali sendiri.
Melihat latar belakang kedua orang tuanya yang sama – sama ulama besar tersebut, tak pelak lagi KH. Mahrus Ali tumbuh dan besar di lingkungan pesantren. Karena itu, tidak heran jika kepribadiannya terbentuk sebagai orang yang shaleh, berbudi luhur dan taat kepada orang tua.
TERSERANG WABAH PENYAKIT CACAR
Perjalanan hidup Rusydi (KH Mahrus Ali) di masa kecil ternyata tidak sepenuhnya nyaman. Cobaan datang silih berganti. Pada waktu menginjak usia 10 tahun, ia terserang wabah penyakit cacar yang cukup parah. Bahkan penyakit itu hampir merenggut jiwanya. Lantaran cobaan ini, terpaksa Rusydi tidak pernah tidur di atas tikar atau kasur. Sebab, jika itu dilakukan pasti kulitnya mengelupas, lekat pada tikar atau kasur. Itulah sebabnya selama sakit Rusydi harus tidur diatas daun pisang yang masih segar. Menurut cerita keluarga terdekatnya, Rusydi menjalani cobaan dengan penuh sabar dan tidak banyak mengeluh. Ia pasrah kepada Allah Swt. Rusydi hanya dirawat di rumah ibunya sendiri, Nyai Chasimah. Ibunya dengan sabar dan penuh kasih sayang menyiapkan daun pisang segar setiap putra kesayangannya hendak tidur. Berkat rahmat Allah semakin hari keadaannya semakin membaik meskipun bekas penyakitnya tidak dapat dihilangkan.
BELAJAR DI PONDOK PESANTREN
KH. Mahrus Ali mulai mengenyam pendidikan sejak ia masih kecil di bawah bimbingan ayahnya sendiri, Kiai Ali. Hingga usianya menginjak 15 tahun, ia berhasil mengkhatamkan al-Qur’an. KH. Mahrus Ali pun belajar kepada ayahnya dalam beberapa bidang ilmu, seperti bahasa Arab, akhlak dan hadits.
Selain mengaji kepada ayahnya, Kiai Ali, Kiai Mahrus Ali juga belajar Agama Islam di bawah bimbingan Kiai Afifi, salah satu pengasuh pesantren Gedongan yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Kepada kakaknya itu Kiai Mahrus Ali belajar berbagai disiplin ilmu, seperti sharaf (sintaksis), Nahwu (tata bahasa), dan Amrithi. Juga kitab Safinah al-Najah dan Sulam al- taufiq. Selama dalam proses belajarnya, berkat kerajinan dan ketekunannya dalam belajar maupun beribadah membuat banyak orang kagum, terutama kakak-kakaknya yang merasa sangat tertarik untuk mengasuh dan membimbingnya.
KALAH DALAM TANDING HAFALAN
Di antara jumlah ilmu-ilmu yang dipelajarinya, ilmu Nahwu dan Shorof adalah kedua jenis ilmu yang menjadi kegemaran Rusydi. Dengan mengerti ilmu ini, pikirnya, ilmu-ilmu yang lain pastilah bisa dipahami. Oleh sebab itu, Rusydi dengan tekun menghafalkan bait-bait Jurumiyah berikut pemahamannya.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan kakak kakaknya, Rusydi terhitung kurang cemerlang terutama dalam menghafalkan bait-bait Jurumiyah. Inilah yang membuat kakaknya, Kiai Ahmad Afifi agak gregetan. Sebab sebagai anak asuh pesantren, dalam hal hafalan Rusydi sering kali kalah oleh teman-teman seangkatannya. Saking kesalnya, Kiai Afifi pernah membentak, “Rusydi. priben si sirane kok bodo” (Rusydi, gimana sih kok bodoh amat kamu ini). Rusydi harus menerima kenyataan itu dengan penuh ikhlas. Hanya ibunya yang tidak setuju jika Rusydi sering dibentak. “Jangan marahi Rusydi terus-menerus, nanti juga bisa mengaji sendiri,” ujarnya kepada Afifi.
Selama belajar di bawah asuhan kakaknya itu, Rusydi belum menunjukkan kecerdasannya. Kiai Afifi terkadang tidak kuat menahan kejengkelannya. Tetapi, karena tidak boleh memarahi Rusydi di depan teman-temannya, Kiai Afifi terpaksa menggunakan cara lain. Rusydi diajak ke sebuah kebun. Di sanalah Kiai Afifi melepaskan kejengkelannya. Namun, Rusydi tetaplah Rusydi, mendapat marah bertubi-tubi, ia tetap sabar. Ia menerimanya dengan hati terbuka. Yang menarik, Rusydi mampu menjadikan kemarahan kakaknya sebagai pemicu semangat. Rusydi semakin rajin belajar. Pikirnya, justru karena ia bodoh maka harus mengaji. Dan benarlah, berkat dari kesabaran dan ketekunannya itu, Rusydi akhirnya berhasil mengkhatamkan beberapa kitab yang dipelajarinya dengan bimbingan kakaknya. Tepat pada usianya yang ke-18, Rusydi mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan menuntut ilmu di pesantren lain. Pondok pesantren pertama yang ia singgahi di luar pesantren Gedongan adalah Panggung, Tegal, Jawa Tengah, di bawah asuhan kakak iparnya sendiri yang bernama Kiai Muchlas.
Kepada Kiai Muchlas, Kiai Mahrus Ali belajar beberapa kitab, diantaranya ia meneruskan mengaji kitab Alfiyah (sebuah kitab yang berisi 1000 bait tentang gramatikal bahasa Arab) karangan Ibnu Malik, Ulama asal Andalusia, Spanyol abad ke-XIV M. Kitab ini merupakan kitab yang belum sempat ia khatamkan di pesantren Gedongan. Di pesantren inilah, KH. Mahrus Ali berhasil menghafalkan seluruh bait kitab Alfiyah dalam waktu yang sangat singkat, sepulang melaksanakan ibadah haji. Ia juga mempelajari syarh Alfiyah (penjelasan kitab Alfiyah), juga kitab Bidayatulhidayah, karya ulama abad ke-VI H, al-Ghazali.
Selain belajar ilmu agama, Kiai Mahrus Ali juga mempelajari ilmu bela diri di kala ada waktu senggang atau tepatnya ketika liburan panjang tiba. Dua orang dan beberapa guru bela diri Kiai Mahrus Ali adalah Kiai Balya, yaitu seorang jawara terkenal asal Tegal Gubuk, Cirebon, Jawa Barat, dan Kiai Muslim, seorang tokoh persilatan dari Wotbogor, Indramayu (Jawa Barat).
Setelah cukup lama belajar di Pondok Pesantren Panggung, Tegal, Mahrus Ali kemudian melanjutkan studinya ke Pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah di bawah asuhan ulama besar bernama Kiai Khalil. Konon, kepergian Kiai Mahrus Ali untuk menuntut ilmu di Kasingan ini dikarenakan rasa malu atas kekalahan dirinya sewaktu adu hafalan Alfiyah. Diceritakan, adalah Kiai Ahmad Afifi, kakak dan gurunya sewaktu di Gedongan yang menjadi promotor terjadinya adu keterampilan tersebut. Sebelumnya, Kiai Ahmad Afifi pernah mempunyai murid yang bernarna Kiai Ma’shum, yang setelah belajar kepada dirinya melanjutkan belajar di pondok pesantren Kempek, Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat. Mendengar kedua mantan muridnya, pada sebuah kesempatan musim libur, Kiai Ahmad Afifi pun mengundang mereka berdua untuk diuji dan diadu keterampilannya dalam menghafal Alfiyah. Pendek kata, Kiai Mahrus Ali menderita kekalahan dari Kiai Ma’shum yang notabene saingan terberat sewaktu masih di Gedongan. Tak pelak, rasa malu, sedih dan motivasi yang tinggi untuk memperbaiki diri menggelayuti pikiran dan hati Kiai Mahrus Ali. Apalagi Kiai Mahrus Ali sempat didamprat dan ditantang Kiai Bilal, Kakak Kiai Mahrus Ali sendiri.
MEMBUBARKAN PERTUNJUKAN LUDRUK
Ada cerita cukup menarik sewaktu di Kasingan. Suatu ketika orang-orang Cina Rembang akan menyelenggarakan pertunjukan Ludruk di Klenteng. Lakon yang akan dimainkan adalah kisah dua tokoh kondang NU, KH. Hasyim Asy’ari dan KH.Wahab Chasbullah yang berada sekitar 1,5 km dari tempat pertunjukan tersebut. Ada sebagian santri yang melakukan unjuk rasa atas pertunjukan itu. Sebagian dari mereka lalu melapor kepada lurah pondok, yang waktu itu dijabat oleh Kiai Mahrus Ali. Sebagai lurah pondok, Kiai Mahrus Ali tanggap terhadap aspirasi santri. Kebetulan waktu itu, KH. Khalil sedang berada di Kudus, sehingga praktis Kiai Mahrus Ali tidak bisa minta pertimbangan gurunya.
Dalam keadaan terpaksa, Kiai Mahrus Ali kemudian mengambil inisiatif sendiri. Sejumlah santri dikumpulkan untuk bermusyawarah. Mereka sepakat untuk membubarkan pertunjukan Ludruk itu. Pasukan santri, dengan komandan. Kiai Mahrus Ali sendiri kemudian bergerak menuju tempat pertunjukan. Tekad mereka bulat, jika tidak bisa dibubarkan para santri siap tempur. Mendengar gerakan yang dipimpin Kiai Mahrus Ali, pihak kepolisian segera menyingkirkan pemain Ludruk dan orang-orang China. Ketika tiba di tempat, pasukan Kiai Mahrus Ali tidak menemukan seorang pun dari mereka, kecuali perkakas Ludruk. Terlanjur terbakar amarah, para santri kemudian memporak-porandakan perkakas itu.
MENGUSIR WANITA TUNASUSILA
Juga masih di Kasingan, Kiai Mahrus Ali sempat mengusir wanita tunasusila (WTS) yang berdomisili di sekitar pondok. Pasalnya, wanita itu bukan saja tinggal di dekat pesantren, tetapi juga menggoda iman para santri. Kali ini bukan fisik yang digunakan oleh Kiai Mahrus Ali, akan tetapi dengan cara lain, yaitu dengan kekuatan batin. Ia mengambil sejumput tanah, dan entah dengan ucapan apa, dilemparkanlah tanah itu ke atap rumahnya. Esoknya, si WTS tadi lari tunggang langgang, hengkang dari rumahnya.
Setelah lima tahun lamanya belajar di Pondok Pesantren Kasingan, Kiai Mahrus Ali, kemudian meneruskan belajar ke Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur di bawah asuhan KH. Abdul Karim, seorang ulama dan pendiri Pondok Persantren Lirboyo serta pernah tercatat sebagai salah seorang murid dari KH. Khalil Bangkalan. Di Pesantren Lirboyo, Kiai Mahrus Ali lebih berorientasi meningkatkan wawasan ilmu agamanya karena ia merasa bahwa ilmu yang telah di peroleh di pesantren Kasingan sudah cukup, atau dalam bahasa pesantren menekuni kesenangannya bermuthalaah. Di samping itu, ia juga sering mengikuti pengajian-pengajian yang sifatnya insidental, seperti “pesantren kilat atau pasaran”. Jika liburan tiba, ia selalu mencari tahu pesantren mana yang membuka pengajian pasaran. Di podok pesantren Tebuireng, Jombang (Jawa timur), Kiai Mahrus Ali sempat mengaji pasaran kepada KH. Hasyim Asy’ari untuk memperdalam beberapa ilmu. Bahkan setelah berkeluarga pun, Kiai Mahrus Ali masih menyempatkan diri menyisihkan waktunya untuk mengaji pasaran sebagaimana sering ia lakukan ketika masih mesantren pada tahun 1950 M. Ia juga pernah mengaji pasaran di pesantren milik Kiai Dalhar di daerah Watucongol, Magelang, Jawa Tengah, sampai suatu ketika ia diangkat menjadi pengasuh Pesantren Lirboyo akhir tahun 1972.
Meskipun menjadi seorang pengasuh, di Lirboyo ia tetap tekun belajar yang dalam tradisi pesantren sering disebut dengan istilah muthala’ah. Bahkan tradisi muthala’ah Kiai Mahrus ini terbilang cukup unik. Betapa tidak, seusai mengaji atau akan mengajar, ia sempatkan kembali untuk membaca kitabnya sebanyak dua belas kali, sekalipun ia sudah paham.
DIAMBIL MENANTU KIAINYA
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Jawa Timur), rnerupakan terminal terakhir perjalanan intelektul Kiai Mahrus Ali. Di tempat inilah ia dinikahkan dengan salah satu putri KH. Abdul Karim yang bernama Zaenab. Awalnya, Kiai Mahrus Ali merasa ragu akan pernikahannya ini. Ia pun kemudian meminta pendapat Kiai Khalil (guru Kiai Mahrus Ali sewaktu di Rembang). Oleh Kiai Khalil ia dinasihati sebagai berikut, “Sudahlah, kalau diminta gurumu jangan macam-macam”. Demikian nasihat Kiai Khalil kepadanya. Kiai Mahrus Ali yang memang masih bimbang itu lantas bertanya “Apa tidak lebih baik di istikharahkan terlebih dahulu?” katanya. Mendengar pertanyaan semacam ini, Kiai Khalil pun berkata: “Apakah istikharahmu lebih baik dari istikharah gurumu?” Mendengar jawaban sekaligus pertanyaan balik itu, Kiai Mahrus Ali terdiam dan langsung meminta izin pulang ke Lirboyo meskipun belum masuk ke rumah Kiai Khalil.
Setelah Kiai Mahrus Ali merasa mantap, barulah akad nikah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1938 M. Ketika itu, yang meng-akad nikah-kan KH. Mahrus Ali dengan Zaenab adalah Kiai Ma’ruf, seorang ulama asal Kedunglo, Kediri, dengan saksi Kiai Abu bakar (Banjarmelati). Dari perkawinannya dengan Nyai Zaenab ini, kiai Mahrus Ali dikaruniai 14 putra yang salah satunya adalah KH. Imam Yahya, sekarang menjadi salah satu seorang pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan Rektor Universitas Tribakti kediri.
Bersambung!
Dikutip dari: Buku 99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid 2 (Pustaka Anda Jombang, 2010)