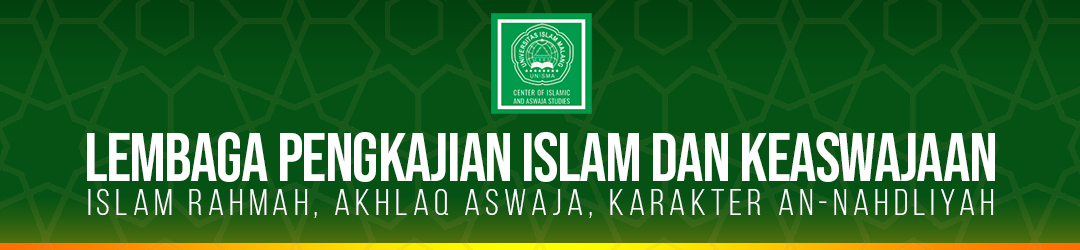Ziarah Pemikiran Gus Dur
Lanjutan (Mengais Perspektif Gus Dur-ian)
Mengais Perspektif Gus Dur-ian
Oleh; Armada Rianto CM
Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Tanah untuk semua
Boleh berantem, tetapi harus tetap menjaga kesatuan, celutuk Gus Dur menimpali banyaknya pertikaian antar golongan, suku, agama dll di negara kita. Komentar kontradiktif ini sangat powerful ketika kita menyadari bahwa kebersatuan berarti keadilan, toleransi, dan membela kebebasan.
Semua yang menyebut diri warga Indonesia harus yakin bahwa “Tanah ini” (negara Indonesia) ada tidak di-setting untuk satu golongan, apalagi satu golongan agama Jika Islam dapat berbángga karena menjadi golongan mayoritas, itu baru terjadi satu abad belakangan ini (atau malah beberapa tahun belakangan ini saja). Sebelum pemerintah memerintahkan mencantumkan jenis agama dalam KTP setiap orang, tidak diketahui pasti berapa manusia yang beragama Islam (atau sebutlah berapa yang beragama). Artinya, marilah kita membayangkan bahwa nenek moyang kita dulu tidak dari sendirinya memiliki agama (apalagi agama Islam Kristen/Katolik). Karena itu tidak fair jika kelompok yang satu mengklaim punya hak lebih dan kelompok yang lain. Di tanah ini.
Sukarno, Hatta, Supomo, Wachid Hasyim, Agus Salim, Maramis, Ny.Santoso, Latuharhary dan the Founding Fathers telah meletakkan pondasi yang kokoh untuk Indonesia bagi semua.
Universal Declaration of Human Rights, aneka piagam dan berbagai produk konvensi PBB sejak berdiri hingga saat ini, Pancasila, UUD 1945, aneka produk ketentuan sidang lembaga tertinggi negeri ini (kecuali perda-perda agamis yang inkoheren dengan konstitusi), semuanya telah menggariskan pemandangan yang sama atas hak-hak dasar manusia.
Di Lembah Karmel, sekelompok orang dengan motivasi tak jelas dengan mengatasnamakan agama tertentu mengklaim diri seakan-akan telah memiliki hak lebih dan sesamanya, bertindak semena-mena terhadap yang lain. Adalah problem kemunafikan konsep-konsep kesalehan yang direduksi pada level paling rendah.
Jika ada kelompok yang takut akan “kemurtadan”. Istilah “murtad” adalah istilah yang memiliki perspektif dan lingkup keluasan penerapan. Jika orang memiliki kegelisahan dalam agamanya dan lantas melepaskan agama itu serta menyebut din “tidak beragama” atau memeluk iman yang lain, bagi kita dan kalangan agamanya menyebut “dia telah murtad”. Tetapi, dalam perspektifnya, dia tidak serta merta bisa kita kutuk karena perbuatannya, sebab dengan itu barangkali dia malah lebih tenang dan mengalami pengalaman spiritual yang menenteramkan dia.
Kontemplasi kegelisahan
Gus Dur adalah sosok yang berani. Bukan dalam kata dan jawaban, tetapi dalam bertanya, kritik-diri, dan kontemplasi. Bahkan kontemplasi tentang apa yang sudah jelas dan sendirinya. Orang beragama sering kali gelisah (terganggu) tentang pertanyaan ateistis, ‘apakah Tuhan ada atau tidak?” Tetapi hampir belum pernah aku mendengar pertanyaan kegelisahan tentang realitas sehari-hari hidup manusia, apakah orang beragama itu ada atau tidak?”
Pertanyaan pertama berkaitan dengan Tuhan. Sedangkan pertanyaan kedua langsung berhubungan dengan realitas manusia. Realitas kita. Pertanyaan tentang manusia merupakan pertanyaan kegelisahan. Karena itu konkret, berurusan dengan kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu, hatiku memang lagi gelisah. Aku tidak menyangkal kegelisahan itu. Humanisme aku pandang memiliki pijakan dan sini. Dari aktivitas menyoal manusia, menyoal dirisendiri. Dalam konteks hidup beragama, apakah manusia yang beragama itu sungguh ada atau tidak. Maksudnya, apakah kita beragama karena kita menghayati nilai-nilai agama dalam hidup ataukah sekedar mengenakan “baju,”“jubah,” “ornamen” formal agama?
Pertanyaan humanis bukan berangkat dan kesangsian. Juga bukan dan keragu-raguan. Tetapi dan kegelisahan. Kegelisahan yang berakar dan keprihatinan. Keprihatinan tentang hidup, hidup beragama. Hidup kita. Hidup bersama kita sebagai manusia-manusia.
Pertanyaan humanis muncul dan kecemasan. Cemas oleh peradaban-peradaban dishumanis (tak manusiawi) yang tiba-tiba hadir dalam bentuk simbol-sirnbol memilukan. Sekaligus mengerikan. Seperti “poso,” “ambon,” “aceh,” “ketapang,” “sambas,” “sampit” (lima kota terakhir pada beberapa tahun lalu), Dalam kegelisahan, mereka bukan lagi nama kota-kota kita yang indah mempesona. Melainkan telah mendadak berubah menjadi simbol-simbol kekerasan yang memilukan. Simbol-simbol kebiadaban, bahkan. Bagi siapa saja.
Kekerasan terasa aneh bila itu rnenyukakan Tuhan. Malah terasa jelas kekerasan menjadi simbol ke-tidak-manusiawian, kebiadaban.
Agama tidak mengajarkan kekerasan
Benar. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Demikian komentar tegas dan seorang sahabat kepadaku. Segala apa yang jahat, seperti tindakan membunuh, menteror, membakar, memusnahkan sesama manusia itu tidak berasal dan agama. Kitab suci dan apapun agama tidak mengajarkan kegampangan seputar kekerasan. Agama itu mengajarkan perdamaian. Bahkan, agama itu sendiri identik dengan perdamaian.
Tetapi, ya tetapi, ada kegelisahan konkret seputar adagium agama itu perdamaian. Apa? Ternyata, para tokoh, pelaksana, eksponen, pelaku, penganjur, pengkotbah ancaman dan kekerasan itu adalah orang-orang beragama. Malah ada yang terkemuka, agamawan intelektual. Mengapa?
Sahabatku tadi menegaskan bahwa mereka itu bukan orang-orang beragama yang baik. Yang jelas, sekali lagi, agama tidak mengajarkan kekerasan Tegas sahabatku dengan penuh keyakinan dan kepastian.
Okeylah agama itu tidak mengajarkan kekerasan. Tapi, apa artinya agama kalau tidak mampu mengajarkan sesuatu yang mencegah tindakan kekerasan? Apakah artinya agama jika tidak melestarikan kehidupan manusia? Apakah maknanya sebuah agama kalau tidak mampu menahan sekelompok manusia (yang beragama itu) untuk memusnahkan sesamanya satu kampung, satu desa, satu wilayah … seperti di ambon, poso, dst.?
Agama, dalam pengertian sahabatku tadi, dan mungkin juga pengertian kita sehari-hari, dipahami secara formal. Agama seakan-akan merupakan realitas lain yang terpisah dan realitas hidup sehari-hari. Jika realitas hidup antar manusia didominasi rasa benci, itu bukan karena agama. Jika hidup sehari-hari dikuasai oleh sikap dendam, itu bukan disebabkan agama. Jika hidup sehari-hari kacau dengan konflik berdarah berkepanjangan, itu tidak ada hubungannya dengan agama. Jika ada teror oleh sekelompok orang, itu bukan karena agama. Agama tidak rnengajarkan semua kejahatan yang menghancurkan kelestarian hidup bersarna.
Oh … aku terus bertanya kepada sang Khalik, apakah artinya agama dengan seperangkat kebenaran tentang-Mu, kalau itu tidak UNTUK melestarikan hidup bersama antar manusia dalam keseharian mereka? Aku terdiam.
Dikutip dari : Buku Gus Dur Sebuah Testimoni Lintas Agama (LAKPESDAM NU Cabang Kota Malang, 2010)