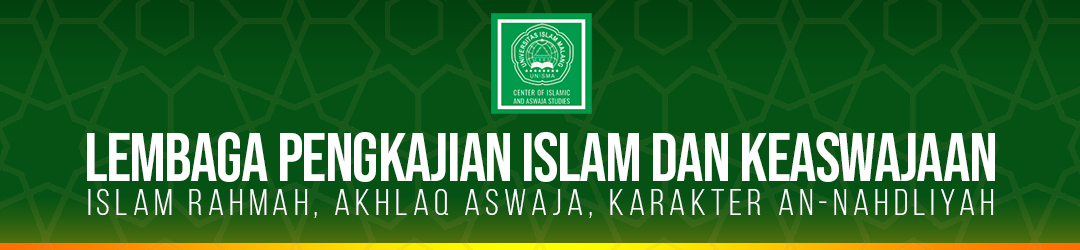Faham ASWAJA
Telaah Tentang Proses Pembentukan dan Tantangannya
oleh
Thoha Hamim
Pembentukan Faham Aswaja
Proses terbentuknya faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah membutuhkan jangka waktu yang panjang. Pengertian istilah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah (Sunni) sebagai sebuah aliran pemikiran (school of thought) tidak dengan serta merta terbentuk dan menjadi baku. Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Sunni dalam bidang teologi, hukum, sufi dan politik terbentuk dalam satu masa, melainkan muncul secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Masing-masing bidang tersebut diformulasikan oleh para ulama yang hidup pada masa yang berbeda pula. Dengan demikian maka faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah akumulasi pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang yang dihasilkan oleh para ulama untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman tertentu. Hal itu dilakukan agar faham Sunni bisa selalu relevan dengan perkembangan baru yang muncul seiring dengan berubahnya waktu.
Penjelasan seperti tersebut bukan berarti faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah tidak memiliki format yang dasarnya belum ada pada masa awal Islam (asr sadr al-Islam). Banyak penulis berpendapat bahwa dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah sudah terformat sejak masa awal Islam, karena ajaran-ajarannya merupakan pengembangan dari dasar pemikiran yang telah dirumuskan sejak periode Sahabah dan Tabiin, yaitu pemikiran keagamaan yang menjadikan Hadits sebagai rujukan ulama. Karena itu para ahli Tarikh al-Tasyri’ menamakan mereka Ahl al-Hadist diberikan sebagai ganti dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah yang pada saat itu masih dalam proses pembentukan.
Sebagaimana diketahui bahwa zaman Sahabat sudah ada kalangan yang tidak menerima hadits sebagai sumber kedua hukum Islam (masadir al-tashri` al-Islam). Otoritas Hadits sebagai landasan penetapan hukum kemudian dipertanyakan oleh kalangan tersebut pada abad kedua Hijrah. Diriwayatkan bahwa al-Syafi`I sering berpolemik (al munazarah) dengan para penolak hadits sebagai sumber hukum kedua tersebut. Diriwayatkan pula bahwa orang-orang Khawarij pada masanya al-Shafi`I menolak keabsahan Hadits sebagai landasan hukum kedua, karena kandungan hadits, menurut analisa mereka, banyak yang saling kontradiksi antara satu dengan lainnya. Argumen yang disampaikan al-Syafi`I untuk menangkis penolakan kelompok Khawarij ini diberi tema “Hikayat Qawl al-Ta`ifa al-Lati Raddat al-Akhbar Kullaha”.
Penolakan serupa juga dijumpai di kalangan Ulama Mu`tazilah, dimana banyak diantara mereka yang tidak mau menerima Hadits baik yang mutawatir apalagi yang ahad, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Namun perlu disebutkan bahwa di kalangan ulama Mu`tazilah masih ada yang menerima Hadits mutawatir walaupun alasan antara seorang ulama dengan lainnya tidak sama. Perlu disampaikan di sini bahwa karena perannya dalam mempertegas fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam maka al-Syafi`I dinobatkan sebagai nasir al-sunnah (penyelamat sunnah). Bahkan dalam memformulasikan ketentuan yang kemudian dipakai sebagai alat untuk membedakan Hadits yang terpercaya dengan yang tidak al-Shafi`I juga menjadi tokoh utamanya. Al-Shafi`I misalnya, adalah ulama yang pertama kali memakai kata musnad sebagai tema pokok untuk koleksi kitab-kitab Hadits.
Dengan latar belakang seperti tersebut maka faham Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah tidak bisa dilepaskan dari kedudukan Hadits sebagai dasar dari setiap diskursus keagamaan yang dilakukannya. Karena itu tidak mengherankan jika faham ini menggunakan kata sunnah, yang merupakan padanan kata hadits, sebagai unsur kata dari makna gerakannya. Para ahli Hadits memang tidak melihat adanya perbedaan antara keduanya. Mereka berpendapat bahwa Hadits adalah narasi dari apa yang dilakukan, dikatakan atau ditetapkan oleh Rasulullah sedangkan sunnah adalah kandungan dari apa yang dinarasikan. Juga tidak mengherankan jika Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah sering diantitesakan dengan dua faham tersebut, terutama faham Mu`tazilah. Pengantitesakan itu tampak misalnya, dalam banyak tulisannya ulama sunni yang merasa perlu untuk menekankan perbedaan antara keduanya.
Hubungan antara Mu`tazilah dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah hubungan antagonistic. Hal ini terjadi terutama pada saat faham Mu`tazilah dijadikan ideology negara oleh Khalifah al-Ma`mun dan al-Mu`tasim dari dinasti Abbasiyah. Doktrin Mu`tazilah yang diperkenalkan oleh dua penguasa Abbasiyah itu mewajibkan semua orang Islam untuk meyakini al-Qur`an sebagai ciptaan (makhluq). Menurut Ahl-Hadits keyakinan seperti itu bisa menggugurkan aqidah karena pemakhlukan al-Qur`an hakekatnya adalah memprofankan kesucian al-Qur`an yang justru terletak pada aspek keabadiannya. Kemudian mereka menuduh bahwa pem-profanan tersebut sengaja diperkenalkan untuk mengesahkan upaya perubahan isi al-Qur`an agar bisa sesuai dengan tuntutan waktu yang senantiasa berubah. Kekhawatiran akan terjadinya implikasi seperti itu kemudian mendorong Ahl-Hadits untuk menetapkan doktrin tandingan bahwa al-Qur`an itu abadi (azali) karenanya bukan makhluq. Seperti diketahui bahwa tokoh yang mempelopori penentangan doktrin yang diperkenalkan oleh al-Ma`mun tersebut adalah Ahmad Ibn Hanbal, seorang yang oleh sebagian ulama dianggap lebih sebagai seorang Imam al-Muhaddithin dari pada Imam al-Madzhab Ibn Jarir al-Tabari, misalnya menganggap Ahmad ibn Hanbal lebih sebagai muhaddith daripada seorang faqih. (jurist consult).
Dikutip dari : Buku “Militasi ASWAJA & Dinamika Pemikiran Islam”/Mei 2001
Penerbit : Aswaja Centre UNISMA MALANG