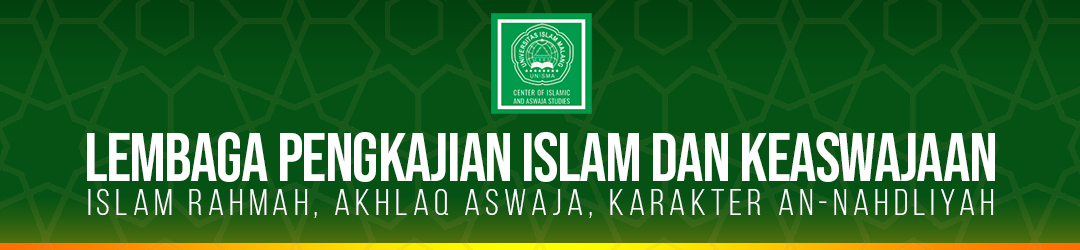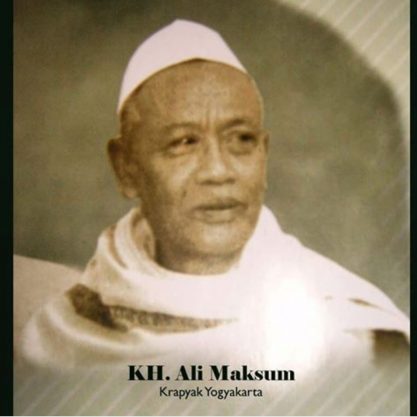99 Kyai Kharismatik NU
KH. ALI MA’SUM
KRAPYAK YOGYAKARTA
WAFAT 1409 H / 1989 M
MENOLAK DISELENGGARAKANYA KONFERENSI GEREJA SEDUNIA DI JAKARTA
Secara syar’i, ajaran agama telah memberikan dasar yang kuat bagi Ukhuwah Islamiyah. Bahkan telah ditetapkan dalam Munas di Cilacap 1947, selain ukhuwah Islamiyah ditegaskan pula adanya Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan antar umat manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan atas dasar kebangsaan). Menghadapi kenyataan hidup yang kompleks, prinsip itu perlu diterapkan dan harus dalam posisinya masing-masing.
Dalamnya juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Kiai Ali berpesan agar umat Islam Indonesia yang paling penting. Dalam artian mau terbuka, memberi dari pada meminta. Meski demikian, Kiai Ali Ma’sum bukan berarti kelompok non muslim bebas berkiprah tanpa batas. Pada tahun 1975-an, ketika terdengar akan menyelenggarakan Gereja sedunia di Jakarta, Kiai Ali membuat menolak melalui surat terbuka yang dikirimkan kebeberapa tokoh agama dan pemerintah. Begitu juga dalam kasus pembahasan RUU Peradilan Agama di DPR tahun 1989, ia tidak habis mengerti terhadap beberapa kelompok, baik di dalam maupun diluar DPR.
Keberadaan umat Islam yang paling dan perananya yang kongkrit dalam perjuangan kemerdekaan merupakan yang fungsional juga memberikan hak-hak politik yang wajar. Prinsip jaminan keamaan bagi Kiai Ali merupakan inti bagi aspirasi politik Islam yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena masalah, masalah Piagam Jakarta dan dasar negara Pancasila pada tahun 1945 maupun asas tunggal Pancasila tidak ditolak oleh umat Islam, khususnya NU.
Meski demikian tidak di ingkari pada masa konstituante NU ikut memperjuangkan dasar negara Islam sebagai proses yang wajar dalam politik liberal. Kiai Ali yang pernah menjadi anggota konstituante memandang bahwa peran politik merupakan bagian kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang tidak boleh diabaikan oleh negara. Dalam membuat perjanjian misalnya, Kiai Ali sering mengutip kata-kata sahabat Ustman bin Affan yang menyatakan bahwa Allah akan menolak (suatu kemungkaran) baik melalui tangan penguasa (yang hal itu), maupun al-Qur’an (Innallaha layaza bi al-Suthan la yaza bi al-Qur’an).
KESADARAN BERNEGARA
Tentang kesadaran bernegara dan berpolitik Kiai Ali sering mengutip tulisan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniyah atau dalam Adab al-Dunya al-Dien tentang beberapa aspek yang menjadi dasar kemaslahatan dunia. Misalnya; 1) Agama yang menjadi pedoman (al-Din al-Munthaha); 2) Penguasa yang berwibawa (al-Shulthan al-Kabir); 3) Keadilan yang merata (al-Adl al-Syamil; 4) Keamanan semesta (al-Aman al-Alm); 5) Kemakmuran sandang pangan (al-Khishb al Darr); 6) Harapan masa depan dan cita-cita yang tinggì (al-Amal al-Fasih).
Sebagai seorang yang menyadari arti pentìngnya politik, Kiai Ali sangat mengajurkan ditegakkannya prinsip musyawarah. “Musyawarah adalah benteng aman dan cela” (al-Masyura hisbn min al-Nadamah wa Aman minal-Malamah), begitulah ia mengutip hadits Nabi tentang musyawarah seperti yang pernah juga dikatakan oleh al Mawardi. Adapun mengenai syarat musyawarah menurut Kiai Ali adalah sebagaimana berikut: Pertama, pikiran yang dikemukakan hendaknya hasil dari pemikiran yang matang dan bertitik tolak dari nilai-nilai Islam. Kedua, Dalam bermusyawarah hendaklah berlandaskan pada itikad baik dan berhati tulus, bersikap terbuka dan tidak angkuh.
ASWAJA BUKAN HANYA MILIK NU
Dari segi keagamaan, Kiai Ali termasuk ulama yang berpandangan luas tentang Ahlus Sunnah waal-Jamaah (Aswaja). Misalnya, tentang sikapnya yang tidak mengklaim bahwa Aswaja adalah hanya milik NU. Pernyataan Kiai Ali ini tentunya sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan Ma’ana Alaíhi wa al-Ashhabi Da’a al-Sawad al-Azham (maka semua golongan yang tidak menyalahi al-Qur’an dan as Sunnah dan pendapat ulama adalah termasuk Ahlu Sunnah wal Jamaah).
Dan kalaulah Kiai Ali ternyata menulis kitab mengenai Hujjah Aswaja dengan membatasi beberapa masalah, maka hal itu bukanlah berarti bahwa ia telah membatasi paham Aswaja hanya pada batas (tau ciri-ciri) tersebut. Dalam buku itu, ia sebenarnya ingin menunjukkan dalil dan istimbat yang menjadi dasar (hujjah) akan masalah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sehingga tidak benar bahwa orang yang mengamalkan Aswaja dikatakan bit’ah; sesuatu yang dianggap sesat atau bahkan musyrik oleh Islam.
Melihat masalah agama secara luas dan mendalam inilah tampaknya yang menjadi pola pandangan Kiai Ali Ma’sum. Ia tidak pernah menyarakan akan tertutupnya pintu ljtihad. Sebaliknya, ia menyuruh umat Islam untuk memandang segala sesuatu dengan secara obyektif. Hanya dalam masalah bermadzhab, baginya adalah sesuatu yang penting dilakukan oleh setiap muslim pada umumnya. Suatu ketika ia pernah mengatakan bahwa “Kalau Imam Ghazali dan Ibn al-Qayyimal-Jauziyah saja bermadzhab Hambali, mengapa kita harus malu mengikuti para imam madzhab?”. Namun begitu, Kiai Ali berpendapat bahwa persoalan madzhab harus dilihat secara proporsional.
BlASA MEMBACA TAFSIR AL-MARAGHI
Dalam sebuah halaqah yang di hadiri oleh para kiai yaitu menjelang Muktamar NU 27, ia menyatakan bahwa para kiai hendaknya tidak membatasi diri dengan apa yang ada dalam teks-teks kitab saja melainkan juga memahami bahwa kitab tersebut ditulis oleh pengarangnya pada suatu kondisi tertentu yang berbeda dengan kondisi sekarang. Adapun maksud dan pernyataan Kiai Ali ini adalah bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini, dimana dalam teks-teks kitab karya ulama dahulu tidak memuatnya, maka tugas kita adalah melakukan ijtihad yang mana dalam ijtihad kita itu bisa dengan mengikuti cara dan dasar ijtihad para ulama masa lalu dengan cara Ilhak.
Dalam hal ini, kriteria al-Kutub al-Mu’tabar yang berlaku di kalangan pesantren dan ulama NU tidak membatasi Kiai Ali dalam mencari wawasan dan perbandingan. Ketika mengajar tafsir Jalalayn misalnya, Kiai Ali juga membawa tafsir al-Maraghi yang mana kitab tersebut dikalangan ulama pesantren dianggap tidak Mu’tahar.
Pandangan dan pemikiran Ali Ma’sum menurut para pengamat memang dikatakan cukup maju. Bahkan dalam beberapa hal pandangan dan pemikiran Kiai Ali nampak begitu berbeda dengan kebanyakan ulama dan kiai pesantren yang menjadi basisnya. Meskipun demikian, berkat keahliannya dalam mengemukakan berbagai pemikirannya yang meskipun berbeda dengan kebanyakan kiai, ia tidak pernah melahirkan perselisihan atau polemik secara terbuka.
Adapun dengan buku keduanya Hujjah Aswaja bahwa Kiai Ali berusaha menjelaskan beberapa masalah khilafiyah yang menjadi pedoman Akidah dan Amaliyah warga NU seperti masalah sampai tidaknya kiriman doa kepada mayat, talqin, tarawih 20 rakaat, penetapan awal Ramadhan, ziarah kubur dan tawashul, yang mana itu semua oleh kelompok “pembaharu” seringkali dijadikan sasaran kritik.
Dalam memandang hal ini, melalui bukunya itu bukanlah dimaksudkan untuk menonjolkan masalah khilafiyahnya tetapi lebih untuk menunjukkan dalil dan pengambilan hukum dari semua masalah itu. “Sudut pandang dan pemahaman ajaran dan hukum agama yang demikian rumit perlu dimengerti sehingga seseorang bisa bersikap toleran dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah,” demikian komentarnya.
Selain menulis buku mengenai Aswaja, Kiai Ali juga menulis buku tentang materi bahasa Arab. Buku yang sekaligus menunjukan bahwa dirinya juga adalah ahli dalam bahasa tersebut juga didasarkan atas hasil pengamatanya dimana ia melihat kenyataan akan sulitnya belajar bahasa Arab baik dilingkungan pesantren maupun di sekolah. Menurut Kiai Ali, bahasa Arab merupakan kunci dalam memahami Islam dari sumber aslinya, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Selain itu, pentingnya bahasa Arab juga adalah untuk mengikuti perkembangan pemikiran yang dihasilkan oleh para ulama.
Maka sebagai bahan pelajaran awal bahasa Arab Kiai Ali kemudian menerbitkan buku Tashrif (perubahan kata). Buku ini sesungguhnya telah ia disusun sejak berada di Termas. Berbeda dengan kitab al-amtsilatu al-tashrifiyyah karya Ma’sum bin Ali Jombang. Buku yang di tulis oleh Kiai Ali ini merupakan metode tashrif dengan sistematika yang lebih ringkas dan praktis karena perubahan kata bisa lebih banyak dengan keterangan dan contoh yang sederhana serta memakai tamrinat (latihan-latihan) yang cocok untuk menguji pemahaman murid.
DIPILIH SEBAGAI RAIS AAM PBNU
Arus perubahan melanda NU menjelang dan di awal tahun 1980-an. Kondisi politik saat itu disamping orientasi dan interes politik praktis di kalangan pengurus, telah mengakibatkan rapuhnya jam’iyah, terutama terabaikannya basis jama’ah pada masyarakat bawah serta kewenangan para ulama. Meskipun tekad mempertegas batas antara NU sebagai jam’iyah dan PPP sebagai partai politik sudah dinyatakan dalam muktamar NU 26 di Semarang tahun 1979, akan tetapi kenyataan ini tidak bisa diwujudkan oleh para pengurusnya.
Dengan wafatnya Rais Aam KH. Bishri Syansuri pada 25 April 1981 betapapun telah membuka peluang bagi sayap politik dan sayap Khittah untuk saling memperkuat posisinya. Selanjutnya, pembicaraan mengenai pengisian jabatan Rais ‘Aam dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kaliurang Yogyakarta pada 30 Agustus s/d 3 September 1981, kiranya menjadi sesuatu yang kian penting dan ternyata dari MUNAS dan Konbes tersebut telah berhasil memilih KH Ali Ma’sum sebagai Rais Aam PBNU.
Kiai Ali sendiri sebenarnya tidak mau diangkat sebagai pemimpin tertinggi dalam NU. Dengan isakan tangis kemudian ia terima baiat dari Prof. KH. Anwar Musyaddad dengan menyetir ucapan Abu Bakar “Inni qad Wullitu’alaikum Walastu bi al-Khairikum, Idza Ra’aitum fiyya’i Wijajah Faqawwimuni Wa’ziluni Watharahuni fi al-Mazhalah“. Meskipun bagi dirinya terasa berat rnewujudkan impian tersebut, terpilihnya KH. Ali Ma’sum ini menandai kemenangan sayap Khittah yang didukung oleh para ulama pesantren dan menciptakan muda. Dalam Khutbah iftitah Munas dan Konbes itu ia menyinggung perlunya regenerasi dan pemulihan posisi ulama sebagai pemegang kendali dalam NU. Dan sejak itu 1angkah-langkah perubahan di NU terjadi setahap demi setahap yang berpuncak pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada akhir tahun 1984. Muktamar tersebut menggantikan NU kembali ke Khittah 1926.
Bersambung!
D kutipan dari: Buku 99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid 2 (Pustaka Anda Jombang, 2010)